Beberapa waktu lalu kantor Batamnews.co.id, Tribun Batam, dan Ulasan Network dikerumuni pengemudi ojek daring. Mereka mengaku mendapat orderan makanan dan antar jemput paket dari kantor-kantor media tersebut. Nyatanya, orderan tersebut fiktif.
Sebelumnya, kantor Tempo di Jakarta dikirim kepala babi dan bangkai tikus. Lalu serangan DDos terhadap suara.com dan peretasan akun whatsapp sejumlah jurnalis dan pemimpin redaksi media.
Tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang tergesa-gesa, kasus teror terhadap media dan jurnalis sepertiya membawa kita mengamini pernyataan “….mereka membenci orang yang menyuarakan kebenaran”.
Namun dibalik semua teror tersebut, ada yang harus dirayakan dan dibersamai. “Jurnalisme Masih Ada”, begitu kira-kira ungkapan polulernya.
Jurnalisme Bukan Untuk Menyenangkan Semua Orang
Dalam sebuah diskusi terkait tantangan jurnalisme, seorang kolega melontarkan pernyataan berikut : “Kalau semua orang senang dengan berita kita, mungkin kita belum bekerja dengan cukup baik. Sebaliknya jika ada orang yang terganggu dengan berita yang kita tulis, kita sudah bekerja dengan baik”.
Benarkah demikan?
Bukan tanpa sebab jurnalis disebut sebagai “anjing penjaga”, sebab jurnalisme idealnya hadir sebagai mata dan telinga publik. Jurnalisme bekerja sebagai otentikator atau pen sahih fakta yang benar dan dapat dipercaya, mengawasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang dan memastikan kebijakan otoritas diawasi.
Kewajiban jurnalisme bukan tentang apa yang publik ingin dengar dan lihat. Namun lebih dari itu, membuat publik tahu dan sadar bahwa berita yang ia baca berdampak bagi hidupnya, yang mungkin bisa jadi membuat hidup jadi tidak nyaman. Jika jurnalisme hanya menyuguhkan berita yang manis, asal bapak senang, sesuai omongan dan tidak menyinggung siapa pun, itu bukan jurnalisme, tapi promosi, propaganda dan hiburan.
Seperti yang ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Menyampaikan kebenaran berarti menyampaikan fakta, data, amatan yang sudah diverifikasi berulang kepada publik. Tujuannya agar publik tahu yang sebenar-benarnya, sehingga mereka mampu membuat keputusan terbaik tentang diri, komunitas dan negara mereka.
Maka jika ada teror terhadap jurnalis, yang terancam bukan hanya jurnalisme, tapi ancaman bagi kebenaran, ruang sipil dan demokrasi. Seperti yang katakan John Dewey “demokrasi cuma bisa jalan kalau masyarakatnya tahu apa yang sebenarnya terjadi “. Jika kebenaran mendapatkan jalan buntu, jurnalisme dibungkam, itu artinya kita betul-betul menuju Indonesia Gelap.
Tantangan Lain, Banjir Informasi
Zeynep Tufekci, seorang sosiolog dan penulis, dalam siniar “Information and Attention in a Networked World “ mengatakan, masalah terbesar dunia saat ini bukan lagi kekurangan informasi, tapi justru kebanyakan informasi yang tidak tertata. Alhasil perhatian publik jadi mudah dialihkan.
Publik hidup dalam rezim scroll. Geser dikit, gawai langsung sajikan ratusan berita, cuitan, utas, dan konten yang menarik perhatian. Tapi ironis, di tengah banjir informasi itu, semakin sulit mencari yang benar-benar penting. Linimasa sesak dengan drama viral, gosip selebritis dan politisi, atau debat receh di media sosial. Kering isu-isu penting seperti kesehatan, pendidikan, atau kerusakan lingkungan. Kondisi ini yang disebut Zeynep sebagai misdirection of attention, atau publik yang teralihkan secara masal.
Kondisi ini sangat disukai penguasa. Mereka akan bisa leluasa mengambil kebijakan tanpa pengawasan berarti dari publik. Tunggu viral baru direspon, lalu buat kebijakan yang tolak ukurnya viralitas. Mereka paham, publik akan segera lupa atau digantikan hal viral lainnya.
Bagi jurnalis, ini justru tantangan besar. Terlebih saat ini antar media bersaing konten viral, clickbait, dan algoritma yang hanya peduli pada engagement, bukan kebenaran. Atas nama ekonomi media, awak redaksi ikut-ikutan mengejar klik, bukan kedalaman. Alhasil berita penting tenggelam, sedangkan isu remeh mendominasi linimasa.
Peran jurnalis dalam situasi misdirection of attention ini tidak lagi hanya menyampaikan kebenaran namun menata ulang fokus publik. Menata ulang berarti merebut ruang diskusi di sosial media dengan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan dan kebaikan publik (bonum commune).
Jurnalisme saat ini tidak cukup hanya mewartakan kebenaran. Ia harus bisa mengembalikan fokus publik, merawat diskusi dan debat publik yang sehat. Jurnalisme juga harus terus jadi watchdog yang mengusik kenyamanan kelompok berkuasa, mayoritas dominan demi kepentingan banyak orang. Karena perubahan tak akan lahir dari rasa nyaman. Dan ini tidak mudah dan beresiko.
Kita Butuh Jurnalis(me) Yang Siap Dibenci
“ Kok media ini cerewet banget, sih?” atau “Kenapa sih harus diungkap-ungkap kayak gini, bikin ribut aja?” Nah, bisa jadi itu tanda bahwa jurnalisme sedang bekerja sebagaimana mestinya.” kata seorang kawan dalam sebuah diskusi.
Memang jurnalis kerap dianggap sebagai provokator, tukang cari masalah dan sok kritis. Bahkan Presiden Prabowo menuduh beberapa media sebagai antek asing. Anggapan ini tentu merugikan jurnalis. Namun dari sisi lain, anggapan ini bisa dimaknai sebagai harga yang pantas dibayar untuk kebenaran dan keberpihakan pada publik.
Jika Prabowo terusik dengan karya jurnalistik, sampai menuduh jurnalis sebagai antek asing. Itu artinya jurnalis telah bekerja dengan baik. Jurnalis telah menyampaikan kebenaran, dan itu mengusik orang-orang yang berkuasa. Sebaliknya jika publik tidak bereaksi apa-apa setelah membaca karya jurnalistik, bisa jadi karya tersebut tidak cukup baik.
Resiko mengatakan, mengungkap kebenaran atau menyampaikan hal yang tidak ingin didengar atau diungkap ke publik, apalagi terkait penguasa atau mayoritas dominan adalah dibenci bahkan dimusuhi. Dalam konteks resiko ancaman terhadap jurnalis, dibenci atau dimusuhi bentuknya bisa teror, intimidasi, gugatan hukum, pemecatan dan bahkan pembunuhan. Jika dengan resiko ini jurnalis jadi tunduk dan diam, dan “asal buat bapak senang” maka publiklah yang rugi.
Agar jurnalisme yang berkualitas tetap ada, tugas publik itu sederhana “beri dukungan”. Dukung jurnalisme yang mengatakan “Ini faktanya, suka atau tidak”. Dukung jurnalisme yang menghadirkan validitas bukan viralitas. Jurnalisme yang berpihak pada publik marjinal dan isu pinggiran, bukan berlindung di balik “jurnalis harus netral dan berimbang” tapi diam-diam menghamba pada kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan.
Seperti kata George Orwell “If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.” Kalau kebebasan itu benar-benar berarti, maka isinya adalah hak untuk bilang sesuatu yang orang lain tidak mau dengar. Itu artinya siap untuk dibenci.
*Disampaikan sebagai bahan diskusi kegiatan SENJA, UKM Pers Mahasiswa LPM Pena Merah UPN Veteran Jawa Timur












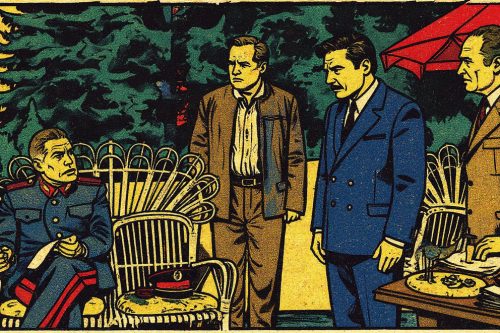

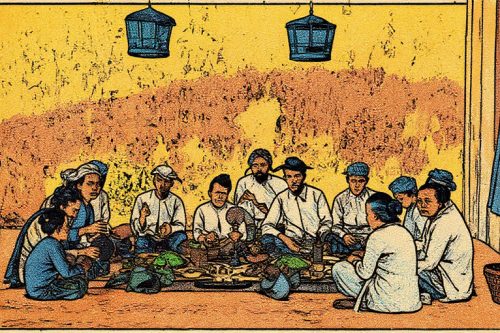

Tinggalkan Balasan