POIN PENTING:
- Pekerja perempuan menjadi minoritas dalam pemilahan sampah.
- Kontrak harian tanpa perlindungan kesehatan memadai.
- Keselamatan dan K3 pekerja perempuan belum diprioritaskan.
Bau menyengat langsung menyeruak begitu saya mendekati gedung dengan papan bertuliskan Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan. Beberapa sepeda motor terparkir hanya sekitar sepuluh meter dari deretan gerobak sampah yang berjajar rapi.
Dua laki-laki tampak bekerja memindahkan muatan sampah dari sebuah gerobak menuju bukaan di dinding depan. Begitu melewati pintu, tampak mesin sabuk angkut (conveyor) memanjang dari bukaan tadi, menggulirkan sampah yang dibongkar dari gerobak menuju tempat pemilahan.
Proses memindahkan sampah dari gerobak ke conveyor berlangsung terus-menerus tanpa henti. Terdapat 23 pekerja di PDU Jambangan, rentang usianya 45–65 tahun. Ada 17 pekerja di area pemilahan dan 6 di area pengomposan. Lima diantaranya pekerja perempuan . Mereka khusus memilah sampah organik dan anorganik.
“Masa kami minta mereka ikut angkat-angkat sampah dari gerobak? Nggak tega,” jelas Hadi Waskito, pengawas PDU Jambangan.
“Tugas berat memang ditangani pekerja laki-laki. Tidak ada aturannya, tapi kami (pengawas dan koordinator) yang menentukan. Soale yo moso tega njaluk ibu-ibu iku angkat-angkat sak mono akehe sampah,” imbuh Dwijo Warsito, Koordinator TPS 3R Surabaya, yang turut berada di lokasi.

Kelima pekerja perempuan tadi menjalankan tugas secara bergantian di area pemilahan awal. Mereka memindahkan sampah dari gerobak sesuai jenisnya: organik dan anorganik. Sampah organik diteruskan lewat conveyor menuju wadah penampungan di sudut ruangan untuk diolah menjadi kompos. Sampah anorganik dipilah lagi sesuai jenis dan kelayakan: kertas, plastik, kaleng, kaca, elektronik, tekstil, dan lainnya. Bahan yang masih layak akan dijual ke pengepul, sementara residu dikirim ke TPA Benowo.
Saat ini ada 12 Tempat Pembuangan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau TPS 3R di Surabaya. Yaitu di Jambangan, Karang Pilang, Warugunung, Tenggilis, Gunung Anyar, Sutorejo, Kedung Cowek, Tambak Wedi, Osowilangun, Banjar Sugihan, Sumber Rejo, dan Bratang.
Menurut situs Pemerintah Kota Surabaya, empat TPS 3R tambahan ditargetkan dibangun pada 2025. “Idealnya, Surabaya memiliki 37 TPS 3R,” ujar Kepala DLH Dedik Irianto.
Dinas Lingkungan Hidup Surabaya menangani empat unit pengelolaan daur ulang sampah yang dilakukan melalui Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos, dan PLTSa. Bank Sampah menekankan partisipasi warga, sedangkan TPS 3R, Rumah Kompos, dan PLTSa beroperasi secara formal di bawah sistem kepegawaian daerah. Pekerja pemilah sampah bekerja berdasarkan kontrak yang diperpanjang dua bulan sekali. Kontrak tersebut mengatur masa kerja, kewajiban, dan hak cuti.
“Dalam sebulan kira-kira ada 4–5 kali jatah cuti, tergantung jumlah minggu,” terang Hadi.
Sistem cuti diatur bergiliran dan maksimal tiga orang dapat mengambil cuti pada hari yang sama. Jika ada pekerja yang membutuhkan cuti tambahan, upahnya akan dipotong.
“Semua pekerja statusnya harian, jadi upahnya juga harian. Kalau izin nggak masuk kerja, ya berarti nggak dapat upah untuk hari itu,” lanjut Hadi.

Warsito menyebut upah harian sekitar Rp160.000, dibayarkan rapel tiap bulan. Dengan 26 hari kerja, pekerja bisa mendapatkan upah Rp4.160.000 tiap bulan. Upah tersebut dipotong BPJS Kesehatan Kelas III dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga upah yang dibawa pulang sekitar Rp4.129.000 tiap pekerja tiap bulan.
Belum ada peraturan resmi mengenai durasi perpanjangan kontrak, sehingga kontrak bisa terus diperpanjang hingga bertahun-tahun. Bahkan ada satu pekerja sudah memasuki tahun kesembilan. Pekerja lama biasnya dipertahankan karena sulit mencari tenaga baru yang mau bekerja mengelola sampah.
” Kalau orangnya rajin dan mau komitmen, kami lebih memilih mempertahankan. Susah. Nggak semua orang mau ngurusi sampah kayak gini,” ujar Hadi sambil tersenyum.
Timbulan Sampah Surabaya
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada 2024 timbulan sampah Surabaya mencapai 1.810,81 ton per hari atau 660.946,82 ton per tahun.
Komposisi terbanyak adalah sisa makanan sebesar 55,48%. Angka tersebut menjadikan Surabaya sebagai penghasil sampah terbesar di Jawa Timur, disusul Kabupaten Malang dan Kabupaten Sidoarjo.
Pada 2023 timbulan sampah Surabaya masih sekitar 1.600 ton per hari. Kepala DLH saat itu, Agus Hebi Djuniantoro, menyebut sampah tersebut tidak sepenuhnya dihasilkan warga Surabaya, tetapi juga berasal dari mobilitas warga penyangga yang bekerja di Surabaya setiap hari.
DLH berkali-kali menyatakan ada penurunan sampah harian 1,5–2 ton sejak terbitnya Perwali No. 16/2022 tentang pengurangan kantong plastik. Namun data menunjukan timbulan justru meningkat menjadi sekitar 1.800 ton per hari dalam dua tahun terakhir. Hingga artikel ini ditulis, tidak ada input data ke SIPSN untuk 2021–2022. Selisih data 2023 dan 2024 juga tidak besar, namun memunculkan pertanyaan tentang akurasi dan kontinuitas pencatatan volume sampah.
Dalam sehari, timbulan sampah di PDU Jambangan bisa mencapai 6–7 ton, sebagian besar dari buangan rumah tangga.

Empat keranjang setinggi dua meter penuh plastik sekali pakai menanti dipilah. Salah satu pekerja perempuan memisahkan tiap jenis plastik dengan cepat. Gunungan plastik itu harus tuntas sebelum jam kerja berakhir.
Bagaimana jika volume meningkat?
“Biasanya yang lain diminta membantu. Misal sudah selesai memilah di conveyor, ya bantu bagian plastik ini. Pokoknya harus habis di akhir jam kerja,” jelas Warsito.
Keranjang harus dikosongkan untuk dipakai lagi keesokan hari.
Perangkat Pelindung
Saat mengunjungi TPS 3R, satu hal yang mencolok adalah ketiadaan perangkat pelindung lengkap. Hampir semua pekerja hanya menggunakan sarung tangan kain, sepatu karet, dan sebagian celemek. Tak satu pun mengenakan masker. Mereka langsung menghirup bau sampah organik dari pukul 07.00 hingga 16.00 tiap hari.
“Sudah biasa,” ujar Tini, salah satu pekerja yang bekerja sejak 2017. “Awalnya ya jijik, ini kan sampah. Tapi lama-lama terbiasa.” lanjutnya.
Menurutnya, masker dan sarung tangan lateks membuat proses kerja lebih lambat. Untuk menghindari kontak langsung, ia memakai sarung tangan kain berlapis.
“Kami menyediakan masker dan mengimbau memakai, tapi mereka bilang bikin panas, jadi nggak mau,” tambah Warsito.
Bangunan pemilahan juga tidak dilengkapi kipas angin. Ruangan tersebut hanya memiliki bukaan lebar dan langit-langit tinggi untuk sirkulasi udara. Namun dengan suhu Surabaya 34–36°C, kondisi itu tidak cukup membantu. Belum lagi uap panas yang keluar dari timbulan sampah.
Para pengawas menyadari adanya risiko kesehatan, namun hingga kini belum ada regulasi yang memastikan pemeriksaan kesehatan berkala. BPJS hanya dapat diklaim ketika pekerja sakit, bukan untuk pencegahan.
“Waktu pandemi COVID-19, kami menangani banyak sekali sampah masker. Tapi alhamdulillah mereka sehat-sehat aja, padahal nggak pakai masker,” ungkap Warsito. Pekerja pemilah sampah termasuk kelompok prioritas vaksin, tetapi setelah itu tidak ada inisiatif pelayanan kesehatan lanjutan dari Puskesmas atau rumah sakit.
Jenis sampah di setiap TPS 3R berbeda. Di TPS 3R Tenggilis ada dua pekerja perempuan khusus memisahkan sampah B3 (baterai, lampu, elektronik, kaleng semprot). Mereka juga tidak memakai masker. Limbah medis tidak diterima karena memiliki sistem pengelolaan khusus.
Namun risiko tetap ada, terutama dari sampah rumah tangga seperti jarum suntik, perban, dan logam berkarat.
“Risiko itu justru sering dihadapi penggerobak,” kata petugas.
Di PDU Jambangan, Tini dan Wahyu menyebut sampah tusuk sate sebagai penyebab cedera paling sering karena tertutup buntalan plastik.
“Kalau sampai tertusuk, darah harus dikeluarkan dulu lalu diobati biar nggak membengkak,” kata Tini.

Penghidupan dari Tempat Sampah
Pekerja TPS 3R berusia 19–60 tahun. Tidak ada aturan batas usia atau jenis kelamin; sejak TPS 3R pertama berdiri pada 2013, rekrutmen menekankan komitmen warga sekitar. Mekanisme ini berjalan di TPS 3R Sutorejo. Namun ketika PDU Jambangan dibuka pada 2016, mencari tenaga kerja ternyata lebih sulit.
“Dulu disosialisasikan ke RT/RW sekitar, tapi nggak ada yang mau. Akhirnya saya minta para pekerja eks-lokalisasi Dolly untuk diberdayakan di sini,” ujar Warsito. Namun tidak semua mampu berkomitmen dan satu per satu mundur. Seiring berjalannya waktu jumlah pekerja bertambah.
Dari 12 TPS 3R, PDU Jambangan memiliki pekerja perempuan terbanyak yaitu lima orang. Di TPS lain hanya satu perempuan, kecuali TPS 3R Warugunung yang sama sekali tidak mempekerjakan perempuan. Di TPS 3R Bratang, pekerja perempuan ditugaskan di rak pengolahan organik berbasis maggot. Pekerja perempuan juga ditugaskan menjaga kebersihan ruang pengawas.
Tini (46) dan Wahyu (46) sudah bekerja lebih dari lima tahun di PDU Jambangan. Mereka sebelumnya bekerja di pabrik korek. Saat Wahyu memberi tahu soal lowongan pemilah, Surtini langsung mendaftar. Ia sendiri justru ragu soal besaran upah harian ke upah bulanan.
“Saya khawatir apa saya bisa pakai gaji bulanan. Kalau di pabrik, pulang pasti langsung terima duit. Kalau bulanan kan enggak,” ujar Wahyu. Ia akhirnya bergabung, setelah pekerjaan di pabrik korek belum ada kejelasan.
“Lebih enak kerja di sini,” ujar Surtini. Wahyu mengamini. Kepastian kerja, upah lebih tinggi, dan suasana kerja yang guyub menjadi alasan utama. Ninik (63) juga merasakan hal sama. Ia tidak menikah dan bekerja untuk menyekolahkan adik-adiknya. Ibunya meninggal pada 2024 dan kini ia tinggal dengan keponakannya.
Pada 2022 Pemerintah Kota Surabaya mengatur penerimaan pekerja TPS 3R hanya untuk warga miskin di sekitar lokasi, agar mereka lebih mandiri dan lepas dari bantuan pemerintah. Rekrutmen dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan.
Namun kebijakan ini membuat pekerja lama tidak dapat kembali. Sebab jika keluar dengan alasan apa pun, termasuk kesehatan, tidak dapat diterima kembali. Seperti yang dialami Tini yang empat keluar karena batuk berkepanjangan. Dulu mudah diterima kembali, namun kini hal itu tidak bisa.
“Tidak bisa masuk lagi, sebab mereka akan jadi cacat hukum jika begitu,” ujar Warsito.

Pengelolaan Sampah Berkeadilan bagi Pekerja
Di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terus mengembangkan program pengelolaan sampah dan fasilitas pendukung seperti Bulky Waste Drop Point, transportasi umum berbayar botol plastik, dan penghasil energi berkelanjutan. Tujuannya mengurangi timbulan sampah secara efisien dan mencegah dampak lingkungan.
Hanya saja, pengelolaan sampah tidak bisa serta-merta dinilai hanya dari statistik, biokimiawi, atau besaran residu, tetapi juga keselamatan pekerja yang memilah sampah. Paparan zat berbahaya dari kontak langsung dengan sampah setiap harinya menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang.
Bagi pekerja perempuan, kerentanan berlapis, karena berada di tempat kerja yang didominasi oleh pekerja laki-laki. Pemerintah wajib mempertimbangkan sistem keamanan kerja untuk perempuan pemilah. Oleh karena itu, pemerintah kota wajib memastikan lingkungan kerja sesuai dengan K3, penyediaan perlengkapan pelindung diri yang layak, dan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan yang rutin dan gratis bagi mereka.
Tulisan ini adalah hasil liputan Fellowship Tata Kelola Sampah di Surabaya oleh WALHI JATIM dan AJI Surabaya. Foto dan ilustrasi oleh Inez Kriya





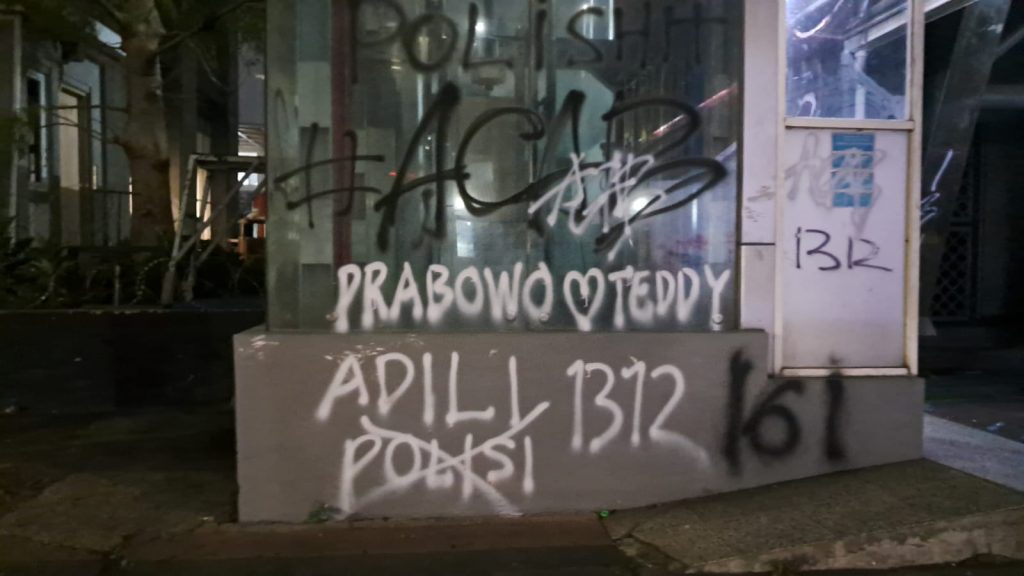









Tinggalkan Balasan